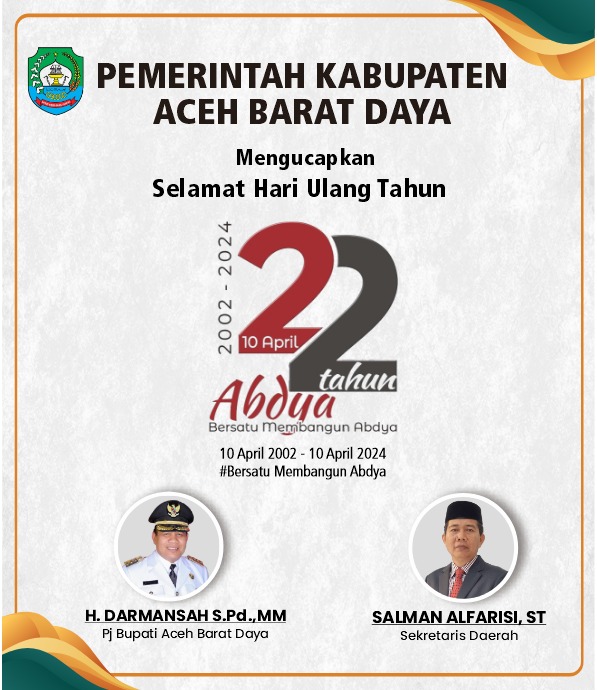IG.NET, BANDA ACEH – Tahun 2022 merupakan tahun penting bagi catatan perjalanan pembangunan perdamaian Aceh. Banyak faktor penyebab dinilai penting menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Faktor utama, sebagai indikator bahwa tahun 2022, adalah tahun penting bagi Aceh.
Indikator pertama, tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya, dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.
Namun sayangnya, para pemangku kebijakan Pemerintahan Aceh sama sekali tidak menyampaikan secara terbuka, perihal sejauh mana capaian yang telah diraih dalam periode itu.
Sehingga, pemerintahan dipimpin pejabat ditunjuk langsung untuk memimpin Aceh, selama penundaan pilkada dapat menyesuaikan kondisi kebutuhan perbaikan-perbaikan pembangunan Aceh, selama mengisi kekosongan pejabat gubernur definitif.
Selanjutnya, Indikator kedua, tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintah Aceh menerima transfer dana otsus, sebesar 2 persen dari dana alokasi umum nasional.
“Mulai tahun 2023, dana otsus Aceh dikucurkan hanya 1 persen dari dana alokasi umum nasional.”
Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana efektifitas penggunaan dana otsus Aceh untuk mencapai efektifitas pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat Aceh?
Hal ini terungkap saat konferensi pers digelar Pokja Lima Masyarakat Sipil Aceh, di Kantor MaTA, Banda Aceh, Selasa 17 Januari 2023.
Pokja Lima Masyarakat Aceh, terdiri dari sejumlah lembaga, yakni MaTA, LBH Banda Aceh, Katahati Institut, WALHI Aceh dan Flower Aceh.
“Berdasarkan catatan Pokja Lima Masyarakat Sipil Aceh, berbelitnya tata kelola Pemerintah Aceh sepanjang tahun 2022,” ujar Koordinator MaTA.
Beberapa hal tersebut adalah:
1. Gagalnya Pemerintah Aceh Menjamin Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum
Sepanjang tahun 2022, setidaknya terdapat tiga kasus penegakan hukum yang berbasis kekerasan, bahkan dua diantaranya masuk dalam kategori extrajudicial killing, namun pelakunya tidak dihukum.
“Perilaku yang demikian, hal ini memperlihatkan bahwa praktik kekerasan oleh aparat penegakan hukum masih terjadi di Aceh dan berlangsung adanya, hal ini sangat bertentangan dengan semangat menjaga keutuhan perdamaian Aceh,” ungkapnya.
2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Aceh
Dalam beberapa tahun terakhir, vonis atau putusan bebas terkesan sudah menjadi tren Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.
Sementara, dari tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2023 tercatat, ada sembilan perkara korupsi yang divonis bebas dengan rincian tahun 2021 ada tiga perkara, tahun 2022 ada lima perkara dan awal 2023 sudah ada satu perkara diputus bebas Pengadilan Tipikor Banda Aceh.
“Hal ini, harus menjadi perhatian semua pihak. Bahwa penegakan hukum belum mengarah kepada upaya perwujudan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat terdampak akibat korupsi,” kata Alfian.
3. Langgengnya Perilaku Perampasan Lahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Buruknya tata kelola lahan pada bidang pemanfaatan sumber daya alam, juga menjadi ancaman serius untuk jaminan ketersediaan tanah di Aceh.
Masalah utamanya adalah masih terlihat nyata ketimpangan penguasaan lahan di Aceh. Lahan pertanahan masih didominasi penguasaan individu dalam skala besar.
Dampaknya, ketersediaan lahan menjadi semakin krisi, yang kemudian memicu laju angka konflik horizontal antara masyrakat dengan masyarakat atau konflik masyarakat dengan perusahan investasi SDA atau bahkan pemerintah dengan perusahaan.
“Bahkan ketersediaan lahan menjadi ancaman keberlangsungan ekologis. Kerusakan lingkungan hidup adalah dampak yang tidak bisa dihindari,” tutur Alfian.
Setidaknya, hingga tahun 2022, angka kasus perampasan tanah rakyat meningkat.
Akibat dari perampasan lahan itu, masyarakat kehilangan 2.634 hektar, wilayah lahan pertanian sebagai sumber ekonomi keluarga.
Tercatat, korban akibat konflik perampasan lahan mencapai 3.779 jiwa.
Selain itu, terdapat 58 orang korban kriminalisasi, dipenjara atas laporan perusahaan akibat mempertahankan tanah kelolanya.
Tidak hanya itu, penderitaan yang dialami oleh masyarakat pun lebih kejam, terdapat 8 orang yang diculik secara paksa, diminta melepaskan lahan yang sedang dikelola.
Selain dari itu, akibat buruknya perilaku perizinan eksploitasi sumber daya alam, sampai dengan tahun 2022, hutan Aceh telah kehilangan 518.440 hektar kawasan hutan.
“Diantaranya, 69.488 hektar kehilangan hutan produksi, 7.077 hektar kehilangan hutan produksi konversi, 12.350 hektar hutan produksi terbatas, 65.780 hektar kehilangan hutan lindung, 36.589 hektar kehilangan kehilangan kawasan konservasi dan 460.609 hektar kehilangan areal penggunaan lain,” jelasnya.
4. Memberi Impunitas bagi Pelaku Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh
Lebih lanjut, pelaksanaan reparasi mendesak korban pelanggaran HAM oleh Pemerintah Aceh tidak sesuai dengan rekomendasi reparasi KKR Aceh. Pelaksanaan reparasi mendesak ini, dilakukan melalui skema bantuan social.
“Artinya Pemerintah Aceh menyamakan hak korban pelanggaran HAM dengan fakir miskin atau korban bencana alam dengan angka setiap korban akan mendapatkan Rp10 juta,” cetusnya.
Padahal, KKR Aceh merekomendasikan reparasi mendesak, sesuai dengan kebutuhan korban. Kekeliruan dalam pelaksanaan ini tentu berdampak sangat signifikan dan tidak bertentangan dengan pertanggungjawaban negara terhadap korban pelanggaran HAM.
“Rekomendasi KKR Aceh tentang reparasi mendesak cukup jelas menyebutkan kebutuhan korban, yaitu korban membutuhkan lima jenis layanan mendesak (bantuan medis, psikologis, bantuan usaha, jaminan hidup dan layanan kependudukan),” ucapnya.
Selanjutnya melalui Keputusan Presiden (Kepres), Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM (TPPHAM) non yudisial, presiden pemerintah sedang berupaya mendelegitimasi hasil kerja Komnas HAM dan mencoba memberi ruang impunitas bagi pelaku.
Ketiadaan upaya untuk mencapai aspek kepastian hukum dalam tugas dan fungsi Tim PPHAM ini dinilai sebagai lemahnya negara dalam melakukan pengenakan hukum yang berakibat pada keberlanjutan impunitas bagi orang atau kelompok yang diduga keras telah melakukan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
“Kasus-kasus pelanggaran HAM berat telah jelas mekanisme penyelesaiannya, yaitu melalui pengadilan HAM. Jika alasan pembentukan Tim PPHAM ini untuk mempercepat pemulihan bagi korban, seharusnya pemerintah justru harus mempercepat adanya peradilan HAM untuk memeriksa kasus-kasus yang telah terjadi,” bebernya.
“Hal ini justru sejalan dengan upaya sebelumnya di mana Komnas HAM telah melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus tersebut,” lanjut Alfian.
5. Gagalnya Mempertahankan Sistem Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pasca Perdamaian Aceh
Terdapat beberapa catatan penting yang berkaitan dengan perkembangan kondisi demokrasi pasca perdamaian di Aceh, diantaranya yaitu:
A. Gagalnya Mempertahankan Ruh UU Pemerintah Aceh
Semakin kelihatan melemahnya Pemerintah Aceh dalam merealisasi pemerintahan di Aceh. Hal ini ditandai dengan beberapa hal. Pertama terdapat beberapa qanun perintah langsung UU Pemerintah Aceh tidak bisa disahkan, karena tidak ada hasil fasilitasi dari pemerintah pusat.
Salah satunya adalah Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan, yang telah difinalisasi oleh pemerintah Aceh sejak tahun 2020, meskipun sudah tiga tahun, pemerintah pusat belum memberikan hasil fasilitasi.
Kedua tidak berfungsinya Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
“Hal ini berdampak pada lahirnya beberapa UU lain pada tingkat nasional yang kemudian terjadi pemangkasan kewenagan Pemerintah Aceh, seperti tentang kepemiluan dan lahirnya UU Cipta Kerja,” katanya.
B. Gagalnya Melakukan Perbaikan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan
Tata kelola pemerintahan yang akuntabel tentu saja diprasyaratkan oleh kondisi keterbukaan informasi yang baik. Namun sayangnya, di saat Pemerintah Aceh mendapat peringkat daerah yang informatif malah jumlah sengketa informasi meningkat dalam setahun terakhir yang menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik masih harus dioptimalkan.
Permasalahan keterbukaan informasi menjadi indikator dan elemen penting sebagai cerminan tata Kelola pemerintahan yangh baik. Di satu sisi, pemerintah pusat mengapresiasi kinerja Pj Gubernur Aceh, namun di sisi lain gugatan terhadap sengketa informasi atau bahkan permasalahan bermunculan pada jantung kuasa yudisial akses informasi yaitu Komisi Informasi Aceh yang tak berjalan efektif.
Hal ini dibuktikan atas gugatan masyarakat sipil terhadap kelembagaan Komisi Informasi Aceh akibat komisioner tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Tidak mampu membangun roadmap fiscal yang semakin rendah. Dengan semakin kecilnya kapasitas fiskal Pemerintah Aceh, pasca menuruntnya proporsi Dana Onomi Khusus dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, mestinya ada kebijakan mendasar dalam skema anggaran yang dibangun Pemerintah Aceh.
“Sayangnya, hal demikian belum terlihat sama sekali. Dalam konteks ini, Pj Gubernur Aceh harus sudah segera menetapkan desaign pembiayaan pembangunan dengan kemampuan fiskal yang berkurang tersebut,” kata Alfian lagi.
C. Unprosedural Pengangkatan Pj Gubernur Aceh
Pengangkatan Achmad Marzuki dalam JPT Staf Ahli Mendagri dilakukan tanpa melalui proses secara terbuka dan kompetitif, sehingga bertentangan dengan Pasal 109 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Jo Pasal 157 Ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diubah dengan PP Nomot 17 Tahun 2020 (PP Manajemen PNS).
Selain cacat prosedur, juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Dimana, pengisian penjabat kepala daerah masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.
“Oleh karenanya, perlu bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10 Tahun 2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sekaligus memberikan jaminan bagi hak asasi warga negara untuk mendapatkan informasi dan berperan aktif terhadap jalannya pemerintahan,” ungkapnya.
6. Melemahnya Kesetaraan serta Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemerintah Aceh gagal dalam melindungi perempuan dan anak. Praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Aceh. Sepanjang tahun 2022, terdapat 1.299 bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kasus kekerasan terhadap anak, terdapat 679 bentuk kekerasan yang didominasi oleh kekerasan seksual. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat 620 bentuk kekerasan yang juga didominasi kasus kekerasan seksual.
“Permasalahan lain, ruang partisipasi perempuan masih sangat sempit di Aceh. Keterlibatan perempuan sebagai partisipasi dalam pengambilan kebijakan masih tidak berjalan dengan baik,” lanjutnya.
“Permasalahan terakhir, pemenuhan hak perempuan sebagai korban konflik masa lalu di Aceh. Perempuan korban konflik tidak mendapatkan hak atas pemulihan fisik secara optimal,” tambah Alfian. (Ril)